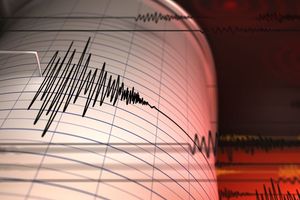“Bukan HIV yang Membunuh, Tapi Stigma” (1)
Di antara orang-orang tersebut, terlihat At (35). Dengan lembaran kertas di tangan, dia mengobrol bersama seorang ibu yang duduk di hadapannya.
At kemudian menuliskan identitas ibu tersebut dan menjelaskan sekilas tentang tes HIV/AIDS. Tiga jam berlalu, acara VCT Mobile Puskesmas Tamblong pun usai.
“Ini salah satu kerjaan saya teh,” ujar At kepada Kompas.com, belum lama ini.
Sejak memutuskan menjadi relawan 2013 lalu, At fokus melakukan pendampingan pada komunitas gay. Salah satunya, meyakinkan mereka untuk tes HIV.
Jika dihitung, sampai akhir Oktober 2018, sudah 400an orang yang ia ajak tes HIV. Dari jumlah itu, sebagiannya dinyatakan positif HIV.
“Saya pegang komunitas gay. Gampang-gampang susah ngajak mereka tes HIV. Ada yang cukup 1-2 kali diajak, mau tes. Itu karena biasanya mereka sadar mereka populasi kunci (berisiko tinggi tertular HIV) dan ingin hidup sehat. Tapi ada juga yang dua tahun diajakin, baru mau dites,” tuturnya.
Meski kadang sulit mengajak tes, ia tidak menyerah. Ia tidak ingin teman-temannya meninggal sia-sia. Sebab HIV bukan akhir segalanya. Pengidap HIV berpotensi hidup dengan baik, salah satunya dengan mengonsumsi ARV.
“Teman saya minum ARV (obat HIV) lebih dari 20 tahun. Dia sehat, bugar, bekerja seperti biasa dan membantu perekonomian keluarganya,” ungkapnya.
Sedangkan temannya yang berhenti meminum ARV, dua tahun kemudian kritis dan meninggal.
Biasanya kasus tersebut ia jadikan penyemangat bagi Odha (orang yang hidup dengan Aids) untuk disiplin meminum ARV dan mengajak komunitasnya tes HIV.
Stigma
At mengisahkan, bagi populasi kunci atau orang yang berisiko tinggi tertular HIV seperti gay, mengikuti tes HIV bukan perkara mudah.
Sebab jika dinyatakan positif, ia harus siap menghadapi banyak hal. Mulai dari mengonsumsi ARV seumur hidup hingga stigma.
“Jadi gay saja sudah mendapat stigma, ditambah lagi dengan HIV positif, stigma yang diterima makin besar,” ungkapnya.
“Padahal, tidak ada yang pengen HIV positif. Tidak ada yang bangga menjadi gay,” tambahnya.
Jenis stigma yang diberikan banyak. Ada yang dicaci maki, dihina, disindir, bahkan diusir dari keluarga karena dianggap memalukan.
Padahal, saat seseorang divonis HIV, dukungan orang terdekat sangat diperlukan. Namun, jika keluarga tidak hadir di saat-saat sulit tersebut, biasanya sesama Odha akan saling menguatkan.
“Kami juga bikin grup di Whatsapp untuk saling menguatkan, mengingatkan agar disiplin mengonsumsi ARV, dan sharing ketika mendapat masalah, terutama tentang HIV,” imbuhnya.
Jika ada yang mengeluh capek minum ARV, At akan berkata, penderita diabetes dan darah tinggi pun minum obat tiap hari.
Jika mengeluh efek samping obat, ia akan berkata, itu hanya sebentar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meminum ARV.
J (22) merasakan manfaat dari grup tersebut. Karena ia belum berani membuka status HIV dirinya terhadap keluarga, ia merasa dikuatkan dengan diskusi di grup atau pertemuan sesama Odha ketika mengambil obat di rumah sakit.
Hal serupa dirasakan An (36). Di tengah stigma yang selalu ia dapatkan, ia merasa dikuatkan oleh dukungan kelompok komunitas, untuk tetap berkarya, menjalankan hidup sebaik mungkin, dan tetap sehat.
Hidup dengan Stigma
An menceritakan stigma yang ia peroleh sejak kecil di tempat kelahirannya Subang. Ia kerap dikatakan banci oleh orang di sekelilingnya.
Saat kecil pula, ia mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari tetangganya.
“Saya mengalami kekerasan seksual dari tetangga. Dia mengancam saya jika bilang ke orangtua. Saya ga ngerti apapun, saya saat itu takut sekali,” ungkapnya.
Sejak kecil, An merasa ada yang beda dengan dirinya. Ia tidak merasa degdegan ketika bertemu perempuan menarik. Lain halnya ketika ia bertemu laki-laki, ia akan merasa degdegan.
Ia sulit menceritakan hal itu. Ia pun bingung harus bercerita pada siapa, karena ia kehilangan sosok ayah, setelah orangtua mereka pisah saat An dalam kandungan.
Menginjak dewasa, An pindah ke rumah ayahnya di Jakarta dan bekerja sebagai marketing. Ia mencoba melawan perasaannya dengan memacari perempuan, namun tak berhasil.
“Saya gagal nikah dengan pacar saya karena dinyatakan HIV positif. Saya pun memutuskan untuk tidak menikah,” ungkapnya seraya mengatakan sudah 13 tahun mengonsumsi ARV.
Tak hanya An, At (35) menjalani hidup dengan stigma, termasuk dari keluarganya.
Kenangan At berputar ke masa kecilnya di Semarang. Sejak kecil, anak kelima dari 12 bersaudara itu sudah merasa berbeda dibanding saudara dan teman laki-lakinya di sekolah.
Ia terbilang cengeng dibanding anak lainnya. Hal ini membuatnya kerap dibully dan dikatakan bencong. Karena tidak nyaman dengan perlakuan teman-temannya, ia tidak memiliki banyak teman.
Hal serupa ia alami pada masa SMP-SMA. Merasa tidak tahan, ia meninggalkan Semarang dan berkuliah di Bogor.
Di Bogor, ia ingin menciptakan sosok yang baru. Ia belajar cara berbicara dan berjalan. Hal itu ia lakukan karena tidak tahan dengan stigma dan kenangan masa kecilnya yang tidak menyenangkan.
Meski berhasil menciptakan sosok baru, namun hatinya tidak berubah. Hingga ia kerap menangis di shalat malamnya, kenapa ia berbeda.
Mencoba melawan apa yang ada dalam dirinya, ia kemudian menikah. Dari pernikahannya hadirlah seorang anak.
Namun pernikahan 11 tahun itu pun kandas. Salah satunya karena At merasa tidak nyaman dengan pernikahannya. Ia selalu merasa ada yang berbeda dalam hatinya.
“Aku memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan mengakui kalau aku gay,” tuturnya.
Tak berapa lama, stigma makin kejam bermunculan. Mantan istri memberi tahu tetangga tentang status At, hingga akhirnya At meninggalkan lingkungan tersebut.
“Keluarga besarku juga menyalahkanku. Aku disebut mempermalukan nama keluarga. Hingga akhirnya aku pun jarang pulang karena tidak tahan dengan stigma,” katanya.
Stigma, sambung At, terbilang berbahaya. Stigma bisa menjadi pembunuh dibanding HIV itu sendiri.
“Saya negatif HIV. Tapi dari pengalaman pendampingan, bukan HIV yang membunuh tapi stigma itu yang membunuh,” ungkapnya.
Bersambung: “Bukan HIV yang Membunuh, Tapi Stigma” (2)
https://regional.kompas.com/read/2018/11/05/09332211/bukan-hiv-yang-membunuh-tapi-stigma-1