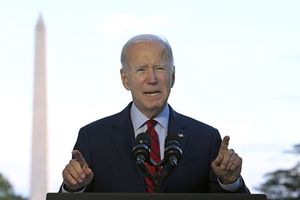Ketika Hanya KJA Jadi Kambing Hitam Pencemaran Danau Toba...
Jika diagnosa masalahnya kurang akurat, maka target dari kebijakan yang ditelurkan akan sangat berpeluang tidak sesuai dengan harapan.
Untuk itulah diperlukan diagnosa masalah yang tepat dan komprehensif sebagai input kebijakan, sebelum kebijakan ditetapkan.
Idealitas proses kebijakan ini nampaknya kurang diperhatikan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan Provinsi Sumatra Utara saat menetapkan KJA (Keramba Jaring Apung) sebagai sumber pencemaran utama di Danau Toba, lalu menginisiasi sektor pariwisata sebagai penggantinya.
Kebijakan yang menganakemaskan sektor pariwisata tersebut, akhirnya mengharuskan usaha-usaha Keramba Jaring Apung yang selama ini telah terbukti berdampak positif khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masyarakat setempat, harus minggir pelan-pelan.
Jika tindak lanjut dari kebijakan tersebut hanya sebatas zonasi atau penataan kawasan, menurut hemat saya, para pelaku usaha KJA akan dengan rela mendukung dan mengupayakannya.
Namun masalahnya, kebijakan tersebut, yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba, serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba, tidak saja tentang penataan.
Isi surat tersebut mengharuskan para pelaku usaha KJA untuk mengurangi kapasitas produksi jauh di bawah kapasitas yang telah berlangsung hari ini.
SK itu menyebutkan daya dukung Danau Toba untuk KJA harus menjadi 10.000 ton per tahun, dengan tujuan agar kualitas air yang disebut tercemar dapat terkendali.
Benang merah atas sengkarut persoalan bisnis perikanan di Danau Toba ini, yaitu kontradiksi data yang dimiliki Pemprov Sumut melalui SK Gubernur-nya (daya tampung 10.000 ton/tahun), yang berbeda dengan data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Selain itu, berbeda juga dengan Tim Riset Care LPPM IPB dengan data terbarunya yang menyatakan daya dukung Danau Toba untuk budidaya perikanan berkisar antara 33.810 ton sampai 101.435 ton per tahun.
Hal tersebut nyatanya didasari atas diagnosa masalah yang kurang lengkap dan kurang mendalam.
Pemerintah pusat maupun provinsi, secara sengaja atau tidak sengaja, menumpahkan semua kesalahan kepada usaha KJA atas pencemaran yang terjadi di Danau Toba.
Padahal, menurut penelitian, justru usaha KJA tidak berperan terlalu signifikan dalam mencemari Danau Toba.
Menurut Ketua Tim LPPM IPB University, Prof Manuntun Parulian Hutagaol, keberadaan KJA bukanlah satu-satunya sumber pencemaran di Danau Toba.
Justru, katanya, ada sembilan klaster lainnya yang memberikan efek lebih besar pada pencemaran yang terjadi di danau tersebut.
Klaster-klaster tersebut antara lain adalah sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba seperti Sungai Asahan, kemudian adanya pelabuhan, pencemaran dari bukit yang berasal dari ladang dan desa, aktifitas peternakan, pemukiman dan hotel.
Setelah itu, barulah sisanya disebabkan oleh KJA rakyat dan dua KJA yang dikelola oleh swasta.
Okupasi KJA atas permukaan air di Danau Toba hanya sekitar 0.4 persen dari total permukaan air Danau Toba.
Jauh bila dibandingkan okupasi KJA di Danau Batur yang diperbolehkan sampai 1 persen dari total luas permukaan.
Parulian juga menyebut, setidaknya ada 120 lebih sungai yang bermuara ke Danau Toba dan membawa berbagai limbah dari ladang, peternakan, pemukiman, hotel dan restoran.
Dengan demikian, selain menertibkan KJA, justru klaster-klaster lainnya tersebut juga harus menjadi fokus pemerintah dalam memperbaiki kualitas perairan Danau Toba.
Dengan kata lain, pemerintah seolah-olah memanfaatkan situasi euforia pariwisata di satu sisi dan euforia anti-pencemaran danau di sisi lain untuk memgambinghitamkan budidaya ikan tilapia/nila yang dipelopori oleh KJA-KJA sebagai sumber persoalan satu-satunya.
Pada konteks inilah saya mengatakan bahwa kebijakan prioritas pariwisata dan beberapa surat keputusan Gubernur Sumatera Utara yang melengkapinya tidak didasari oleh diagnosa masalah yang lengkap dan adil.
Dengan hanya menjadikan budidaya ikan tilapia via KJA-KJA sebagai kambing hitam, lalu pemerintah langsung banting setir kepada sektor pariwisata dan meminggirkan sektor usaha perikanan tilapia secara pelan-pelan.
Padahal, kebijakan tersebut tidak disokong oleh diagnosa tentang sumber pencemaran Danau Toba secara detail.
Pemerintah menutup mata pada sumber-sumber pencemaran danau lainnya yang proporsinya jauh lebih besar dibanding usaha perikanan tilapia.
Kemudian juga soal surat keputusan gubernur yang mengubah status danau dari mesotrofik menjadi oligotrofik.
Surat keputusan tersebut tidak konsisten dengan kebijakan yang memprioritaskan sektor pariwisata di Danau Toba.
Karena, status oligotrofik untuk danau nyatanya mengharuskan peruntukan airnya hanya untuk air minum.
Jadi secara regulasi, surat keputusan gubernur tersebut bukan hanya melarang usaha perikanan via KJA-KJA, tapi kegiatan pariwisata di atasnya pun semestinya tidak diperbolehkan.
Artinya, jika pemerintah daerah konsisten, maka surat keputusan gubernur tentang status Danau Toba bisa dijadikan acuan legal untuk memprioritaskan segala rupa usaha pariwisata di Danau Toba.
Tapi nyatanya yang muncul ke permukaan, pemerintah justru menggunakan surat keputusan tersebut sebagai kekuatan legal komplementer atas kebijakan pemprioritasan pariwisata di Danau Toba, yang secara prinsipil bertentangan dengan substansi status danau.
Jadi kembali kepada perspektif kebijakan publik tadi, pertama, pemerintah menelurkan kebijakan pemprioritasan sektor pariwisata di Danau Toba yang tidak didukung oleh diagnosa persoalan yang tepat dan akurat.
Sehingga, sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, pemerintah terkesan mengambinghitamkan sektor perikanan tilapia sebagai penanggung dosa utama dari pencemaran di Danau Toba.
Padahal KJA-KJA tidak berperan signifikan dalam menciptakan pencemaran.
Ada banyak klaster pencemaran yang justru tidak dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menata Danau Toba.
Dengan kata lain, pemerintah sudah melakukan keteledoran kebijakan publik mulai dari proses awal pembuatan kebijakan, yakni input kebijakan yang tidak akurat.
Kedua, imbas lanjutan dari diagnosa yang kurang akurat tersebut, pemerintah daerah mengubah status danau dari mesotrofik menjadi oligotrofik yang justru tidak konsisten dengan kebijakan besar pariwisata yang disodorkan pemerintah pusat.
Perubahan status danau menjadi oligotrofik menyebabkan danau sekaligus tidak bisa disentuh oleh usaha pariwisata, hanya bisa untuk sumber air minum.
Inkonsistensi antara kebijakan besar pariwisata dengan surat keputusan gubernur di atas memperlihatkan betapa buruknya proses pengambilan kebijakan pariwisata untuk Danau Toba, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.
Hal penting lain yang sepatutnya dipertimbangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah selain KJA milik perusahaan yang jumlahnya tak lebih dari 1000 unit.
KJA milik masyarakat yang jumlahnya hingga 14.000 unit sangat mendominasi bisnis perikanan air tawar di Danau Toba ini.
Tentu saja, nasib 12.000-an manusia menjadi hal yang tidak boleh dipertaruhkan secara sembrono utamanya di kala pandemik masih menjadi momok semua sektor.
Sebagai pemerhati, saya juga berharap bahwa hasil kajian ke depan dapat lebih otentik dan mampu mengakhiri polemik data yang ada.
Demikian pula bisnis perikanan sesungguhnya dapat disinergiskan dengan kegiatan sektor pariwisata.
https://regional.kompas.com/read/2022/01/22/070839078/ketika-hanya-kja-jadi-kambing-hitam-pencemaran-danau-toba










![[HOAKS] Foto Ikan Raksasa di Danau Hogganfield pada 1930](https://asset.kompas.com/crops/k61Jxb0rnf1AjoftSCvVz9fGnS4=/0x0:750x500/170x113/data/photo/2021/12/09/61b22443e24a9.jpg)