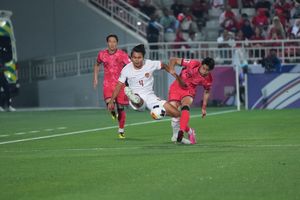Kehidupan Eks Tapol di Kendari, Bebas tetapi "Terpenjara"

KENDARI, KOMPAS.com – Tubuhnya kurus dan jalannya gontai, usianya sudah menapaki 81 tahun, Lambatu namanya. Pria uzur itu sudah 37 tahun menjadi penghuni lokasi penampungan bekas tahanan politik terkait PKI di kampung Nanga-Nanga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Siang itu, Lambatu terlihat sedih, gubuk yang ditempatinya sejak 1978 nyaris roboh. Alhasil, Lambatu terpaksa menopangnya gubuk itu dengan anakan kayu (dolken) di bagian depan dan bagian samping gubuk reot tersebut. Bantuan rehabilitasi rumah dari Kementerian sosial untuk warga miskin tak diterimanya. Kesedihannya bertambah, setelah mengetahui alasan yang menyebabkan dia tidak mendapat bantuan tersebut.
"Pendataan baru-baru ini di Nanga-Nanga, informasinya rumahku tidak diperbaiki karena lahannya bukan saya yang punya. Saya ini punya sertifikat tanah dari BPN yang dikeluarkan tahun 2008, seperti teman-teman yang lain," tuturnya, Kamis (1/10/2015).
Kampung Nanga- Nanga dibuka pada 1978, oleh 42 kepala keluarga bekas tahanan politik peristiwa 1965, luasnya sekitar 1.000 hektar. Mereka dibebaskan setelah sempat dipenjara tanpa surat penangkapan dan tanpa diadili. Kampung Nanga-Nanga hanya berjarak 20 kilometer dari ibu kota Sulawesi Tenggara, Kendari.
Saat ini hanya terdapat sekitar 20 rumah di tempat itu. Sebagian besar masih berbentuk asli seperti ketika dibangun 37 tahun silam. Rumah ukuran 6x8 berdinding papan dicat putih beratap seng campur rumbia, dengan satu jendela di bagian depan dan dua jendela di bagian samping.
Dari 42 orang yang membangun tempat itu, kini hanya tersisa dua orang eks Tapol di kampung tersebut. Mereka adalah Lambatu dan Fauzu (73) serta beberapa janda para eks tapol PKI. Sisanya telah meninggal dunia dan memilih keluar dari kampung tersebut. Pada 2010, listrik baru dapat dinikmati di kampung itu setelah sebelumnya mereka hidup tanpa fasilitas air bersih dan penerangan.
Lambatu, pria kelahiran Kapontori, Kabupaten Buton itu, di zamannya, mungkin adalah satu-satunya pemuda Buton yang paham betul ideologi komunis. Pengetahuan itu diperoleh Lambatu ketika secara diam-diam menikmati buku-buku karya Karl Max dan pemikiran Lenin saat bekerja paruh waktu sebagai penjaga perpustakaan di kota Ujung Pandang (nama lama Makassar).
Dia sempat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 1959. Pemahamannya terhadap paham Marxisme pula yang membuat Lambatu kemudian bergabung dengan partai komunis. Pada 1964 Lambatu menempati posisi sekretaris komite subseksi CSS Partai Komunis Indonesia di kecamatan Kapontori, Buton.
Di Kapontori, Lambatu menjadi seorang guru SMP. Ia aktif membangun kelompok diskusi tentang bagaimana memajukan negara dan memberi pendidikan politik kepada warga di daerah asalnya.
”Politik Buton terjadi dua kutub. Buton itu kan sisa-sisa kerajaan, pusat kerajaan di sana. Inilah yang perlu kita tantang. Kita menggalang front yang baik, kerja baik dalam pronasakom itu kerja baik, utuh itu yang kita herankan,” katanya.
Gelombang penangkapan
Situasi mulai memanas ketika PKI disebut-sebut sebagai dalang peristiwa berdarah pada 30 September 1965. Lambatu semakin khawatir ketika pemerintah mengumumkan PKI sebagai partai terlarang. Ia kemudian ditangkap pada 1970 bersama ribuan orang yang dituduh menjadi anggota dan simpatisan PKI di Sultra.
“Kita dijemput tentara katanya mau diamankan, ternyata kita tidak pulang-pulang. Dalam tahanan kita disiksa, disetrum, dipukul, ditindis pakai meja selama beberapa hari untuk menjawab pertanyaan mana dokumennya, struktur PKI seperti apa?” kenang Lambatu.
Di Sulawesi Tenggara, penangkapan pertama terjadi pada 18 Oktober 1965. Delapan pimpinan PKI ditahan Korem 143. Disusul tindakan lain berbau kebencian yang menyebar secara cepat di provinsi ini dan menyebar berbagai kabupaten lain. Pada 1968, 200 orang yang dikategorikan anggota PKI dipenjara.
“Saya tak bisa tidur mendengar semua itu. Terlebih lagi karena Buton disebut-sebut sebagai pemasok senjata bagi Partai Komunis,” kata Lambatu.
Wa Ode Zatimah, istri Lambatu bahkan sampai demam sejak penyisiran anggota partai dilakukan. Lambatu mengatakan, dia tak pernah memikirkan hidupnya akan berubah. Ia menenangkan istrinya dan mengatakan musuh partai komunis hanyalah imperialisme dan feodalis, yang lainnya tak ada.
Namun Lambatu keliru. Pada 7 November 1965, sejumlah petugas masuk ke rumahnya. Istrinya berdiri gemetar. Anggota militer itu mencari dokumen yang terkait dengan kudeta. Tak menemukan dokumen, Lambantu digelandang ke markas militer malam itu juga.
Dia kemudian mengalami penyiksaan fisik dengan interogasi hingga berbulan-bulan lamanya dengan pertanyaan yang sama hingga Ia tak bisa berpikir. Mengapa masuk PKI? Mana dokumen-dokumennya? Struktur PKI seperti apa? dan pertanyaan lain yang membuatnya tercengang-cengang tanpa bisa menjawab.
Ia dijebloskan ke penjara Buton hingga 1970 tanpa surat penahanan dan pengadilan. Lambatu mengingat, interogasi dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari pagi hingga tengah malam dengan pertanyaan yang sama.
”Dengan penyiksaan dipukuli sehingga banyak korban, keluarga saya turut jadi korban. Meskipun mereka di luar. Karena pemaksaan dalam mencari dokumen-dokumen, sehingga diadakan penggeledahan di dalam rumah. Dalam penggeledahan itu terjadi pelanggaran seksual dari petugas waktu itu terhadap istri saya,” dia mengisahkan.
Akibat kejadian itu, istrinya menderita stres dan akhirnya meninggal dunia pada 1976. Untuk mengetahui siapa yang salah dan benar dalam peristiwa itu, menurut Lambatu, pemerintah meluruskan sejarah.
“Hidup seperti apa ini tak bisa lagi berpikir. Saya hanya ingin ini segera berakhir, Jangan sakiti istri dan keluargaku,” tambah Lambatu.
Akhirnya berita melegakan tiba pada 1969, ketika Pangdam VII Wirabuana, Andi Azis Rustam dan Oditur Militer Kolonel Busono dan Kolonel Bagyo dari Direktorat Kehakiman Pusat memutuskan Buton tak terbukti menjadi kawasan pemasok senjata buatan China untuk PKI.
Namun setelah siksaan dan pemenjaraan bertahun-tahun yang mematikan jiwa ratusan orang itu, kabar baik tersebut datang sangat terlambat. Penangkapan dan penyiksaan itu, bukan saja menjadi kenangan gelap yang senantiasa melintas dalam hidup para mantan tahanan politik itu, tapi juga menjadi catatan buruk untuk para anak cucu mereka yang ikut menderita dan disisihkan dari pergaulan selama berpuluh-puluh tahun.
Termarjinalkan
Kondisi termarjinalkan itu dirasakan Ambardin. Dia diasingkan lingkungannya karena sang ayah, La Ode Hadidi juga dituduh terlibat dengan PKI saat menjadi kepala mantri kesehatan se-Wakatobi.
Ambardin mengenang, saat bapaknya ditangkap, ia baru berumur dua tahun sehingga dia sebenarnya tidak memahami situasi politik saat itu. Namun, setelah masuk sekolah dasar dia dikucilkan dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak lain yang orangtuanya tidak terlibat dengan komunisme.
”Seperti anaknya tentara. Kalau ingin dia mau pukul kita, tidak segan-segan mereka. Asal dia melihat itu, eh anaknya PKI itu, langsung dia buru kita. Seperti keluarga dekat itu banyak yang sudah tidak mengakui lagi, bahwa itu keluarga saya. Apa lagi dia sebagai PNS, polisi dan tentara itu sangat takut sekali,” kata Ambardin.
Akibat stigma negatif itulah, Ambardin tak pernah memiliki cita-cita lagi. Sebab, pemerintah melarang anak-anak anggota PKI menjadi PNS atau pekerjaan pemerintahan lainnya. Bahkan hanya untuk mengurus KTP saja, Ambardin selalu dihambat.
Pengalaman pahit serupa juga dirasakan Fauzu yang mulai menghuni penjara pada 1966. Sama seperti yang dialami Lambatu, Fauzu juga menderita siksaan selama menghuni penjara. Akibatnya, salah satu matanya kini buta.
”Kalau terbukti memang saya terlibat dalam perkara ini, saya rela dihukum mati dibunuh di tempat. Saya tanda tangan dengan darah saya sendiri dari pada disiksa," ujarnya.
Penyiksaan mulai berkurang pada 1970, dan tak lama kemudian mereka dinyatakan bebas namun masih harus menjalani masa isolasi di tempat lain. Pada suatu malam di tahun 1970, dengan menggunakan kapal laut bernama Sultra, puluhan eks tapol asal Buton diangkut ke Kendari.
Mata mereka ditutup kain agar para eks tapol tidak tahu lokasi tujuan mereka selanjutnya. Setibanya di Kendari mereka digiring ke kamp pengasingan di Ameroro, Kabupaten Konawe. Selama di Ameroro, mereka juga mengalami penyiksaan. Tapi tidak separah seperti saat di dalam penjara Buton.
Hingga 22 Desember 1977, sebanyak 175 tapol PKI golongan B ditahan di Ameroro. Selain di kamp pengasingan Ameroro, beberapa tapol juga ditahan di kamp pengasingan Pudotoa, Lepo-Lepo dan Tinggololi, Kendari.
Kampung Nanga-Nanga merupakan lokasi pengasingan terakhir bagi para eks tapol PKI. Lahan tersebut merupakan hadiah dari Pangkopkamtib Sudomo waktu itu. Mereka mendapat surat izin penggarapan lahan yang ditandatangani komandan korem setempat.
Surat izin penggarapan adalah pengganti sertifikat, jika ada yang mempermasalahkan lahan tersebut. Awalnya, lahan itu diperuntukkan bagi 500 tapol golongan B se-Indonesia Timur. Namun, hanya 42 orang tapol asal Buton, Muna, Kendari, Wawotobi, Kabupaten Konawe, Kolaka dan Makkasar yang bersedia bermukim di kampung Nanga-Nanga.
Ternyata tidak banyak yang tahan dengan kondisi dalam kampung tersebut. Kampung itu seperti penjara kedua buat mereka. Mereka mampu bertahan dengan membuka lahan dan menanam ubi. Namun, jerih payah mereka kerap sirna karena terlebih dahulu disantap babi hutan.
Apabila hujan deras, mereka terpaksa berjalan kaki dengan air sepinggang untuk membeli beras dan begitu tiba di pasar sebagian pedagang memilih menghindar karena takut melayani mereka yang sudah dicap PKI itu.
Kini, Lambatu biasa didatangi mahasiswa semester akhir yang melakukan wawancara untuk bahan pembuatan skripsi. Selain itu, ia juga masuk 15 orang eks tapol yang akan menyusun buku berjudul "Memecah Pembisuan" yang dikoordinir Ilham Aidit, anak mantan Ketua Umum PKI, DN Aidit.
"Dari LIPI juga pernah mendatangi saya di rumah ini untuk wawancara sebagai bahan riset," papar Lambatu.
Lambatu menyesalkan beberapa adegan film "Pengkhianatan G30S/PKI" yang semasa pemerintahan Orde Baru selalu diputar setiap tahun. Dalam film ini, rapat persiapan kudeta militer digambarkan dihiasi kepulan-kepulan asap rokok yang keluar dari mulut para anggota PKI. Hal itu, ujar Lambatu, dianggap tidak sesuai dengan paham PKI.
“Di PKI kita dilarang merokok, karena rokok itu candu. Kita juga dilarang beristri dua, karena satu istri saja belum tentu bisa adil,” paparnya.
Bebas namun "terpenjara"
Meski mendapat tempat tinggal baru, namun Lambatu dan para eks tapol merasa terisolasi. Dengan status "mengerikan" yang mereka sandang, maka para bekas tahanan itu tak bisa bepergian dengan leluasa.
"Kami tidak boleh ke mana-mana. Kartu tanda penduduk (KTP) kami juga diberi kode ‘ET’ yang artinya eks tahanan politik. Isolasi itu baru dibuka di masa pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. Kami di sini sangat berterima kasih pada Gus Dur (panggilan Abdurrahman Wahid)," ujar Lambatu.
Kini Lambatu berharap, Presiden Joko Widodo bersedia meneruskan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dan merehabilitasi semua orang yang terkait dengan PKI. Hal senada juga diungkapkan Fauzu, mantan sekretaris Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI) cabang Buton.
Meski sudah dinyatakan bebas dari tahanan, lanjut Fauzu, tapi negara saat itu masih tetap mengawasi semua aktivitas para tapol PKI. Buktinya, mereka masih berstatus tahanan rumah karena hingga kini belum terbit surat atau dokumen yang menyatakan mereka sepenuhnya telah bebas.
“Masih kesulitan anak kami menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS. Ada proses screening sehingga keturunan kami harus mengganti nama agar bisa sekolah dan mendaftar sebagai PNS,” paparnya.
Semestinya, kata Fauzu, anak cucunya tidak ikut terbebani dengan persoalan masa lalu. Kini, mereka menuntut pemerintah untuk memulihkan status politiknya setelahi Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000 mencabut Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme/Leninisme di Indonesia.
Langkah ini dilakukan Gus Dur karena mempertimbangkan HAM semua orang termasuk eks tapol PKI. Sementara itu, SM Bihina, mantan anggota DPRD Kendari yang juga anggota PKI pada 1965 mengatakan dirinya pernah bertemu dengan mantan ketua Komnas HAM RI, Ifdal Kasim saat berkunjung ke Kendari pada 2011 lalu.
“Saya dijanjikan anggota Komnas HAM saat itu untuk memperjuangkan rehabilitasi atau pemulihan nama baik kami, karena sampai sekarang stigma pengkhianat terhadap negara masih ada,” kata dia.
Walaupun proses untuk mendapatkan rehabililtas sangat panjang dan membutuhkan kesabaran, dia tetap berharap dia bisa memulihkan nama baik para eks tapol PKI. “Sepanjang waktu keturunan kami pasti akan dicap pengkhianat negara. Padahal kebanyakan dari kami tidak pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan, lalu gaji pensiunan kami sebagai PNS tidak pernah dibayarkan sampai sekarang. Bahkan harta benda kami juga dikuasai negara dan tidak pernah dikembalikan,” ujar Lambatu.
-
![]()
GP Ansor: Negara Tak Perlu Minta Maaf kepada PKI
-
Jokowi Yakin Pemberontakan seperti PKI Tak Akan Terjadi Lagi
-
Polri Sudah Kantongi Identitas Penyebar Fitnah Presiden Jokowi soal PKI
-
![]()
Kisah Tujuh Gubernur yang Dituduh Terlibat Gerakan PKI Dibukukan
-
Purnawirawan TNI-Polri Dukung Jokowi Tak Minta Maaf soal PKI























![[HOAKS] Video Gempa di Majene Sulawesi Barat](https://asset.kompas.com/crops/8Ff2JspS-YHfn6XPOTvjmYCUGWI=/0x320:2000x1654/170x113/data/photo/2019/08/17/5d57b8fbcb3bb.jpg)